Wanita yang Memilih Langit
Boleh jadi di seluruh Indonesia Ida Pandita Empu Budha Maha Rsi Alit Prama Daksa merupakan sulinggih termuda kini. Saat didiksa tanggal 14 Maret 2007, usianya baru 21 tahun. Usia yang terlalu dini dan begitu muda untuk seorang diksita. Tapi apa arti usia saat “suara langit” memilih lain. Yang gelap akan menjadi terang, yang pekat akan menjadi cair, tentu.
Sejatinya tidak ada kebetulan dalam hidup. Keberuntungan dan nasib apes diatur oleh karma. Semua tergantung padanya -- masa kini menentukan masa depan, masa lampau menentukan nasib kini. Setidaknya inilah yang disadari Maha Rsi Alit ketika langit menentukan lain jalan hidupnya.
Dara kelahiran 13 Maret 1986 tentu tak merasa memilih jalan sunyi nan terjal itu. Namun tak terhindarkan, karma pula yang menentukan tanggung jawab ini. Karma pula yang menggedor-gedor pintu batin Maha Rsi Alit memasuki dunia sunyi ini. Bukannya tanpa alasan Maha Rsi Alit akhirnya menentukan jalan hidup berbeda dengan orang kebanyakan. Jawaban paling misteri tentu karena ia ingin membebaskan sosok gaib seorang Maha ibu.
Siapa gerangan maha ibu yang telah dibebaskan Maha Rsi Alit? Hanya Maha Rsi Alit yang tahu, tentu. Yang jelas sebagaimana penuturannya, sosok ibu gaib inilah yang senantiasa menemani perjalanan sunyi itu. Sosok ibu gaib ini pula yang senantiasa membimbingnya, membesarkan hati manakala gundah kelana menohok-nohok. “Berkat maha ibu itu ego saya disadarkan. Berkat ibu itu pula batin saya diteguhkan,” papar Rsi Alit tersenyum.
Siapa sebenarnya Maha Rsi Alit yang penuh fenomenal itu? Tentu ia bukan sosok yang jatuh dari langit. Saat sebelum didiksa menjadi sulinggih Maha Rsi Alit tak lebih dari gadis biasa. Tak ada tanda-tanda ia memendam mujizat, apalagi menunjukkan hal luar biasa. Ibu-bapanya memberi ia nama Ni Komang Widiantari. Nama yang sejak tujuh tahun lalu tak lagi disandangnya – karena kini setelah didiksa menjadi sulinggih ia mesti memakai nama diksa.
Rsi Alit, begitu ia akrab disapa bukan berasal dari keluarga brahmana apalagi keturunan para Empu sebagaimana umum di Bali. Tidak juga berasal dari keluarga pemangku. Buyut, kakek, hingga ayah kandungnya adalah seorang petani. Saban hari akrab bergaul dengan tanah. Belakangan, Sang ayah I Nyoman Pandan, dan sang ibu Ni Mudana beralih profesi sebagai peternak ayam. Di tengah-tengah keluarga petani inilah Rsi Alit dilahirkan -- dibesarkan di tengah aroma tanah huma, di Banjar Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
Masa kecil Ni Komang Widiantari senantiasa gundah dalam keluarga kecilnya. Ayah-ibu sering cekcok, dan bila ngambek ibu kerap pulang ke rumah orang tuanya. Musibah ini menimpa Widiantari kecil bertubi-tubi, sampai-sampai tak pernah merasakan indahnya masa kecil sebagaimana anak-anak lain di desa. Bila sedang ngambek, tidak siang tidak malam Widiantari senantiasa digendong ibu ke mana pergi, kadang tinggal di tegalan sepi sembari menangis celegukan, menahan rasa lapar dan haus.
Cinta sang istri Ni Mudana bertepuk sebelah tangan, ternyata. Di usia begitu belia, sang ayah kawin kembali, kondisi keluarga pun jadi tambah ruwet, kacau balau. Pandan telah menyakiti seorang ibu yang telah melahirkan anak-anaknya. Menginjak kelas IV SD Widiantari tinggal di rumah nenek. Nyaris sempurnalah derita dialami Widiantari kecil, tak sempurna mereguk kasih sayang. Tumbuh dan besar dalam ketidakakuran keluarga, dibasahi rasa sesak dan linangan air mata.
Karena hari kelahiran sama dengan ibu kandung, dipercaya bisa menimbulkan petaka, Widiantari lalu dijadikan anak angkat sang paman, saudara ayah sendiri. Apa lacur, menginjak usia 12 tahun, sang ayah kandung I Nyoman Pandan keburu meninggal, mati mendadak tanpa ada gejala sakit. Ini cobaan yang tidak bisa diterima Widiantari. Pandan meninggalkan anak-anak saat usia masih tergolong muda, masih produktif, seputar umur 40 tahun.
Berkat jasa ayah angkatnya, Widi akhirnya menyelesaikan pendidikan di SMP di Susut, Bangli. Tahun 2005 tamat di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri I Bangli. Hanya ini jenjang pendidikan yang sempat ditempuhnya. Saat di SMK ia sempat menjalani pertukaran pemuda di Belawan, Medan, Provinsi Sumatra Utara. Pernah mengikuti lomba mengarang berbahasa Inggris se-Indonesia, dan lolos dalam kategori 100 pengarang terbaik. Sesaat setelah tamat sekolah menengah, harapan Widi hanya bekerja dan bekerja, mencari uang dan mencari uang. Cita-cita idealnya cuma satu, menjadi pengarang berbahasa Inggris.
Demikian, setelah meraih ijazah di SMK ia rarud menuju Bintan, Provinsi Riau Kepulauan. Maunya ia bekerja di sini. Sayang setelah tiga bulan magang, panggilan sebagai karyawan tetap di sebuah hotel tak kunjung tiba. Entah kenapa di Bintan hatinya senantiasa gundah, pikirannya tak karuan, kerja tak kunjung diterima.
Syukur, beberapa bulan ia bisa tinggal di rumah keluarga, kendati tak keluarga dekat. Tapi hatinya kian dibuat kering, sebentar-sebentar ingin pulang ke Bali. “Ya saya betul-betul tidak welcome di situ. Bisikan untuk senantiasa pulang selalu mengiang di hati,” ingat Rsi Alit tercenung.
Suatu malam ia tidak bisa menolak keinginan untuk pulang. Uang di dompet cuma tersisa Rp 600.000, sementara ongkos tiket pesawat ke Bali Rp 875.000. Ia bingung, seharian hanya bisa menangis di kamar. Dalam himpitan haus dan rasa lapar ia berdoa, memohon kelak ia bisa pulang. Pagi-pagi ia kemas semua pakain, jam satu siang tiba di Bandara Batam. Dadanya kian sesak karena uang cuma tersisa enam ratus ribu. Di mana lagi hendak dicari?
Syukur seorang sopir taxi, orang Batak, kenalan dekat keluarga di Bintan memberi uang tiga ratus ribu. Tiket bisa dibeli, akhirnya. Saat transit di Bandara Cengkareng, Jakarta, tiba-tiba saya terima telepon dari Bintan, mengabarkan lamaran kerja diterima. “Aduh ini tidak jodoh, kenapa justru saat saya balik keputusan baru diterima. Ya, saya lupakan pekerjaan itu, saya lupakan Bintan, saya putuskan untuk pulang, pulang, dan pulang,” tandas Rsi Alit penuh senyum.
“Jam tujuh malam pesawat tiba di Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Tapi entah kenapa saya masih punya sisa duit dua ratus ribu. Saya lega rasa lapar segera terobati. Dijemput keluarga, sebelum pulang saya habisi uang itu sembari keliling kota Denpasar,” kenang Rsi Alit sembari ketawa kecil.
Tapi di rumah pun Ni Nyoman Widi senantiasa resah. Yang ada di benak hanya kerja, kerja dan kerja. Tapi toh setiap lamaran tak pernah mengena. Widi nyaris putus asa dan senantisa ketakutan. Suatu saat pas sandikala, sore menjelang petang, ia datang ke kuburan, mengadu di pusara sang ayah. Tapi soal tak jua pernah selesai. Saban hari setiap pulang ke rumah ia selalu histeris, berteriak-terik ketakutan. Kadang merasakan diri seperti macan kelaparan. Keluarga jadi bingung, Widi sempat dibawa kesejumlah orang pintar, hasilnya tetap nihil.
Berbulan-bulan Widi mengalami “histeria,” badannya tambah kurus, mukanya kian pucat, pikiran tak pernah stabil. Suatu hari ia bertemu Mangku Bawa dari Desa Petak, Gianyar. Sosok inilah yang membantu menenangkan pikiran Nyoman Widi, menyadarkannya, memberinya petuah. Secara berangsur-angsur ia disuruh melakukan meditasi. Anehnya, dalam meditasi ia bisa meronta-ronta menangis, ibarat induk macan kelaparan. Setelah dilukat, disucikan dengan air suci, gejala ini lumayan mereda. Tapi toh rasa takut dan hati yang gundah belum terobati.
Demikian bila hatinya tengah sejuk Widi senantiasa melakukan meditasi. Tiba-tiba dalam meditasi itu terbayang seorang dewi. “Saya melihat dengan mata hati, dewi ini tergantung pucat, seperti mayat tak berkedip. Ia memohon pada saya untuk membebaskannya. Semata hanya ingin membantu, saya bebaskan dewi itu. Ia cantik, baik hati, penuh olas asih, dan selalu memberi nasihat. Saya disadarkan olehnya, dan saban meditasi selalu membimbing saya,” kenang Rsi Alit.
“Kak sujatine tiang niki sapasira,” ini pertanyaan yang diajukan kepada Mangku Bawa setelah Widi mengalami kejadian-kejadian tak biasa. Pekak Bawa cuma menjawab singkat, “Dirimu adalah dirimu, Ni Komang Widiantari.” Tapi siksaan mental nyaris menemui tragik puncak, pada satu titik ia jadi takut pada diri.
Demikianlah, saban ia pejamkan mata dalam meditasi, ia mendengar bisikan madiksa, madiksa. “Saya tidak tahu apa arti kata madiksa, lagi pula saya tidak pernah berpikir menjadi sulinggih. Saya menolak, saya tidak bisa mengambil tugas itu. Tapi mendadak saya pingsan. Entah kenapa ketika saya “mati,” roh saya melihat diri saya seperti mayat, terjengkang, kaku dan pucat. Saya pikir hari itu saya akan mati. Suara gaib dari dalam hati terus saya dengar, menuntut kesediaan untuk madiksa. Aduh, saya takut mati, saya terpaksa mengiyakan desakan itu. Satu setengah jam mati, akhirnya saya terbangun,” papar Rsi Alit runtut.
Pernah suatu ketika dalam meditasi ia diajak menari, dibawa terbang seseorang, naik dan naik, yang ditemui cuma ruang kosong dan kosong. Saat hendak turun ia betemu jembatan, titi ugal-agil, yang ia lihat hanya juluran tangan-tangan seperti orang kepanasan. Mereka merengek minta tolong. “Saya tidak tahu, apakah ini disebut neraka, tapi keadaannya sungguh menakutkan,” ujar Maha Rsi Alit.
“Setelah berkali-kali “mati”, lebih dari delapan kali, Widi menyatakan kesanggupan madiksa. Saban duduk terpusat, ia mengaku didatangi Batara Lingsir Siwa Pasupati di Srokaden, Desa Abuan. “Saban hari beliau datang membimbing saya. Awalnya saya awam pada dunia ini, tapi berkat bimbingan Batara Lingsir saya jadi mengerti, mantra dan mudra Buddha secara otomatis. Hal itu datang dari dalam hati saya. Ketika saya menyatakan sanggup, beliau bersedia menjadi nabe. Kini semuanya terserah beliau. Terkadang Maha ibu gaib junjungan saya juga datang, memberi nasihat penuh kelembutan.
Histeria, ketakutan pada diri sendiri memang tak pernah muncul lagi. Widi merasa lebih gampang melakukan perjalanan ke dalam. Ia malah sangat gampang bila hendak mohon petunjuk dari Batara Lingsir atau kepada Mahaibu. “Susahnya kemudian, apa yang harus saya katakan kepada keluarga besar, saat usia semuda ini hendak madiksa? Saya jadi bingung juga,” tuturnya.
Untuk kepentingan masyarakat, ia perlu pengakuan formal, keluarga sepakat mencari guru nabe secara sekala. Kali ini ia datang pada seorang Pedanda Buda di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Karangasem. Walau sang pendeta mengagumi kemampuan Ni Nyoman Widiantari dalam melakukan mudra dan merapal puja - semua percis mudra-mudra Budha. Ida Pedanda menolak menjadi guru nabe – alasannya: Ida Pendanda tidak memiliki hubungan secara paguron-guron, lagi pula Widiantari tidak berasal dari keluarga Brahmana.
Setelah perjalanan melelahkan, Widi akhirnya bertemu Ida Pandita Mpu Acarya Prama Daksa, dari Geria Padang Tegal, Ubud, Gianyar. Ida Pandita menyatakan kesanggupan menjadi guru nabe. Setelah didiksa ia pun amari aran, berganti nama Ida Pandita Empu Budha Maha Rsi Alit Prama Daksa.
Gelar ini sesungguhnya semata untuk kepentingan formal, sebab jauh sebelum didiksa, Batara Lingsir Siwa Pasupati yang berstana di Srokaden telah menganugerahi panggilan Maha Rsi Budha. Kenapa berisi Budha? Menurut Rsi Alit, mustahil bertemu Siwa jika Budha di dalam hati belum ditemukan. Budha itu adalah keheningan hati, jika hati hening Siwa pasti mendekat. Sebab sesungguhNYA Dia tidak ke mana-mana, Dia tetap di dalam diri ini.
Menjadi Fajar untuk Semua
Cantik dan terhormat, bijak dan lembut hati. Boleh jadi dia sosok wanita paling bahagia sekarang ini. Di usia sangat muda ia disucikan jadi sulinggih, sebuah tanggung jawab yang pada awalnya dia tolak. Tapi setelah direnungi, semua tugas akan sempurna pada tempatnya. Dulu ia bercita-cita ingin kaya, punya rumah bagus, punya mobil mewah. Saya berpikir dengan hidup berkecukupan saya bisa bahagia, tapi kini yang terjadi justru sebaliknya. “Saya telah salah dengan pikiran-pikiran itu, semua itu ternyata tidak langgeng.” Ujar Rsi Alit lembut.
Saat memasuki jenjang kependetaan, Ida Pandita Empu Budha Maha Rsi Alit Prama Daksa memang tidak pernah mempersiapkan tugas itu. Sejak dulu di masa sekolah dia tidak senang dengan pelajaran agama, apalagi yang bersifat hafalan, justru itu ia kini susah menghafal mantra yang tidak nyambung dengan bisikan hati. Praktik ini mirip dengan orang berdeklamasi, semata hafal kata-kata saja, sementara hati tak kuasa menghidupkan. Bagi Rsi Alit, mantra adalah bisikan hati terdalam, ia bukan yang dihafal.
“Kini memang saya seorang sulinggih, tapi saya merasa masih banyak yang harus saya bersihkan dari pikiran ini. Pikiran yang kotor, kemarahan, kedengkian adalah musuh utama yang harus dikendalikan terus. Jika itu tidak dibersihkan, ketulusan, kelembutan, kesejukan hati tak mudah tumbuh di dalam batin. Itulah hakikat Budha, bersih tercerahkan, sehingga hati menjadi fajar bagi sang diri, dan menjadi fajar untuk semua.
Tangkil ke Griya Siwa buddha salain, Buda Kliwon Ugu, pujawali ring Merajan Ida Rsi Alit.
#by Wayan Westa

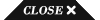

Mengharukan, mengagumkan. Apalagi kisah ini ditulis orang yang sudah mumpuni seperti bapak Wayan Westra. Sepengetahuan saya, memang ada kejadian-kejadian seperti itu walaupun tidak persis sama, seperti yang dialami oleh adik ipar, keponakan dan beberapa orang teman/sahabat. Oleh karenanya, sayapun sangat mempercayai bahwa reinkarnasi benar adanya dan yang reinkarnasi tidak harus dari keluarga atau keturunan kita sendiri. Dan apa yang kita lakoni saat ini, tidak terlepas dari sebagai apa kita dulu, apa profesi kita.
ReplyDeleteKisah hidup masa kecil beliau, sama dg khidupan kecil tiang, hingga saat ini tiang sakit tdk kunjung sembuh, kadang dkatakan histeris sndri dkamar. Mungkin ini karma buat tiang tdk tau bagaimana tiang dikehidupan sbelumnya.
ReplyDelete